Oleh Anita Rachman
Wacana-edukasi.com, OPINI–Hari ini sebanyak 15,9 juta jiwa anak di Indonesia mengalami fatherless atau setara dengan 20,1% dari total 79,4 juta jiwa anak yang berusia kurang dari 18 tahun. Dengan kata lain, dari setiap 5 anak di Indonesia, 1 di antaranya mengalami fatherless (detik.com, 17/10/2025).
Mengutip dari berbagai sumber, tidak hadirnya figur ayah ini ternyata berdampak serius pada aspek emosional, psikologis, sosial hingga akademis anak. Secara emosional dan psikologis anak akan merasakan cemas atau depresi karena tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orangtua. Kondisi ini dapat mempengaruhi rasa kepercayaan diri dan ketrampilan anak dalam bersosialisasi. Dampak selanjutnya performa akademis pun menjadi tidak optimal.
Dr Rahmat Hidayat, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada mengatakan, ketidakhadiran ayah baik secara emosional maupun fisik menyebabkan anak kehilangan role model dalam berperilaku. Baik dalam pengendalian diri, kedisiplinan, interaksi sosial serta sikap bertanggungjawab (detik.com, 17/10/2025).
Fatherless bukan hanya berarti sang anak tidak memiliki ayah karena sudah meninggal. Namun ada juga karena ayah dan ibu sudah bercerai dan tidak ada lagi komunikasi. Bahkan ada juga kondisi keluarga masih utuh, ayah masih ada, hadir secara fisik, tetapi minim atau bahkan tidak ada interaksi secara emosional dengan anak. Meminjam istilah psikolog anak Bunda Elli Risman, “ayah ada tapi tiada”. Terbukti dari total 15,9 juta anak fatherless, 11,5 juta di antaranya ternyata tinggal bersama ayah, namun ayahnya menghabiskan waktu 60 jam per minggu alias lebih dari 12 jam per hari di luar rumah untuk bekerja.
Berbagai langkah penyelesaianpun ditempuh, di antaranya; program edukasi pranikah, pemberian hak cuti suami untuk mendampingi istri setelah melahirkan, program ayah mengantar anak ke sekolah hingga pemerataan lapangan kerja. Namun ternyata solusi-solusi tersebut tak jua membuahkan hasil. Hal ini karena solusi tersebut tidak menyentuh akar masalah, tapi hanya di permukaan saja karena hanya menyelesaikan sebagian masalah dan sifatnya pun sementara.
Dari fakta yang ada, pemicu fenomena fatherless selain memang karena faktor individu ayah, juga dipengaruhi faktor sosial dan ekonomi yang ternyata ujungnya erat kaitannya dengan peran negara.
Secara individu, adalah fakta bahwa hari ini belum semua ayah memahami peran dan kewajibannya secara utuh. Banyak yang masih memahami tanggungjawabnya hanya mencari nafkah. Seorang ayah merasa sudah menyelesaikan tugasnya ketika telah mencukupi kebutuhan materi, termasuk biaya sekolah anak-anak.
Pemahaman individu yang rendah ini tidak lain karena sistem pendidikan yang tidak mendukung. Pendidikan hari ini gagal menyadarkan individu tentang siapa dirinya. Jangankan memahamkan fitrah bagaimana menjadi laki-laki, suami dan ayah, pendidikan hari ini fokus menuntut siswa untuk belajar dan mengejar ilmu dunia agar siap masuk ke dunia kerja. Terbentuklah mindset sekolah ya hanya untuk bekerja mencari uang. Bahkan dalam meraih itu semua tidak ditanamkan pemahaman halal-haram, haq dan batil sehingga individu terjerumus pada kebebasan tanpa batas.
Pendidikan agama yang mampu menyadarkan individu bahwa dirinya adalah hamba Allah dan harus menjalani kehidupan sesuai dengan aturan Allah, justru ditinggalkan. Inilah sistem sekulerisme yang menjadi asas pendidikan hari ini. Maka, lahirlah ayah-ayah ada tapi tiada, lahirlah keluarga-keluarga fatherless.
Hasil didikan sekulerisme ini pun akhirnya membentuk masyarakat yang juga sekuler. Membentuk opini umum di tengah masyarakat, bahwa tugas mendidik anak di rumah ada pada ibu. Apalagi ibu punya lebih banyak waktu bersama anak di rumah. Akibatnya terjadilah normalisasi, bahwa kondisi tersebut wajar, tidak ada yang salah alias lumrah.
Selanjutnya, faktor ekonomi ternyata cukup dominan menjadi penyebab tidak hadirnya ayah karena harus bekerja. Bahkan sekalipun ayah paham tentang perannya, tuntutan keadaan ‘memaksa’ ayah tak punya banyak pilihan kecuali harus tetap keluar rumah. Ketika terjadi kasus perceraian yang menyebabkan anak terpisah dari ibu dan atau ayah pun faktor tertingginya adalah karena ekonomi. Di mana suami tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, di sisi lain mencari pekerjaan begitu sulitnya.
Kondisi ekonomi seperti ini muncul karena roda perekonomian digerakkan atas dasar kebebasan. Siapapun bebas memiliki apapun tanpa melihat halal-haram. Dampaknya, orang kaya bebas menumpuk modal hingga bisa membeli dan menguasi apapun; tanah, tambang, perusahaan, pabrik, termasuk fasilitas umum. Merekapun dengan mudah menghasilkan uang dari uang. Sementara orang miskin sama sekali tidak punya akses, kecuali hanya sebagai pekerja.
Mirisnya, negara menjadi pelayan oligarki karena sebelumnya telah membiayai para pejabat negara mendapatkan kursi. Lahirlah kebijakan yang menguntungkan para oligarki, seperti privatisasi sumber daya alam, pajak rendah untuk korporasi, impor besar-besaran. Di sisi lain rakyat kecil, dalam hal ini ‘ayah’ ditekan habis-habisan. Harga kebutuhan naik tapi upah tak seimbang. Akses pendidikan dan kesehatan tak merata. Akhirnya ayah ‘dipaksa’ bekerja banting tulang peras keringat, pergi pagi pulang malam karena semuanya harus ditebus dengan uang. Inilah kejamnya sistem kapitalisme.
Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan sistem Islam, di mana roda perekonomian dijalankan di bawah koridor syariat. Seluruh kebijakan dalam pengelolaan dan pendistribusian kekayaan negara menggunakan standar halal-haram. Tidak ada kebebasan kepemilikan sebagaimana dalam sistem kapitalisme. Jauh dari monopoli, intervensi apalagi kompromi dengan segelintir elit. Negara benar-benar menjalankan perannya mengurusi urusan umat.
Pendidikan dalam Islam adalah salah satu kebutuhan pokok, oleh karena itu negara sebagai pengurus rakyat akan berusaha sekuat tenaga mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses seluruh rakyat secara merata, mudah, murah bahkan bisa saja gratis. Ekonomi negara yang kuat meniscayakan terwujudnya kondisi ideal ini.
Sementara itu, tujuan dari pendidikan adalah untuk mencetak pribadi yang beriman dan bertaqwa. Ayah yang beriman dan bertaqwa paham betul bagaimana menjalankan peran sebagai suami dan ayah. Memimpin dan bertanggungjawab atas seluruh anggota keluarganya, lahir-batin, spiritual maupun material, dunia hingga akhirat.
Pun terkait ketersediaan lapangan kerja, tidak diserahkan kepada swasta dan pasar sebagaimana hari ini. Tetapi negara hadir memastikan setiap laki-laki yang siap bekerja, mudah mendapatkan pekerjaan. Islam juga menjamin upah yang adil dan layak karena perhitungannya bukan didasarkan suplly and demand tapi disetarakan dengan manfaat kerja atau nilai jasa yang diberikan.
Jelaslah bahwa fatherless bukan semata persoalan individu, melainkan problem sistemik. Yaitu dampak dari penerapan sistem sekuler-kapitalis yang kemudian merusak tatanan kehidupan di semua lini, ya individu, ya sosial, ya pendidikan, ya ekonomi. Jadi, tidak cukup dengan solusi parsial dan pragmatis, tetapi harus memastikan sistem yang digunakan sudah benar dan itu tidak lain adalah Islam.
Views: 16





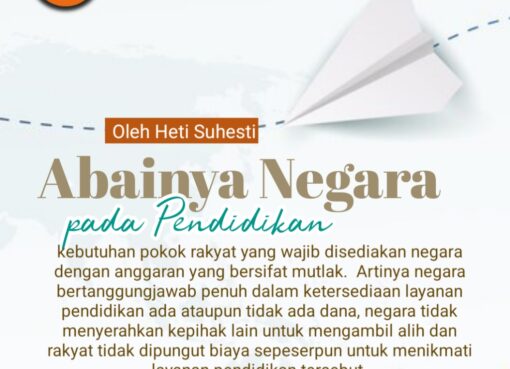
Comment here